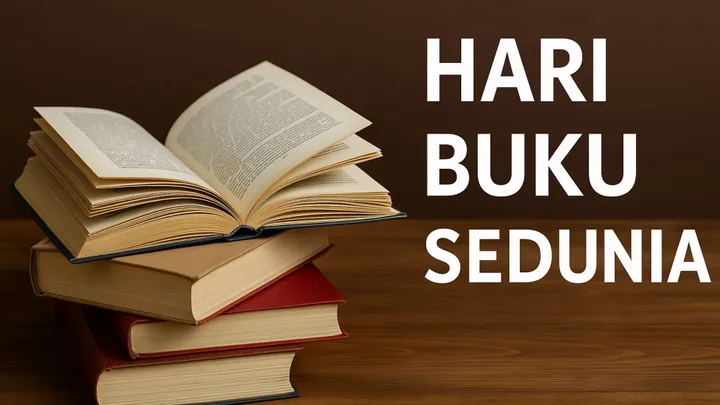Hari Kartini, Aku masih ingat jelas hari itu. Tanggal 21 April, dan aku datang ke kantor pakai batik biru cerah — hasil buru-buru di pasar minggu sebelumnya. Saat masuk, kulihat beberapa rekan kerja perempuan pakai kebaya, dan para pria berbatik formal. Ada tumpeng di ruang tengah, poster Hari Kartini besar-besar, dan backsound lagu “Ibu Kita Kartini” versi akustik yang diputar berulang.
Tapi satu hal bikin aku terdiam sebentar: di ujung ruangan, duduk seorang office girl yang sehari-hari biasa tersenyum padaku, kali ini mengenakan kaus oblong dan celana hitam biasa. Saat aku tanya kenapa nggak ikutan “kartinian”, dia cuma jawab pelan, “Aku malu, Mbak. Baju bagus cuma satu, itu juga dipakai pas nikahan adik kemarin.”
Dan di momen itulah aku sadar, Hari Kartini itu bukan tentang baju adat, bukan tentang lomba fashion atau sekadar pose Instagram. Tapi soal sesuatu yang jauh lebih dalam.
Kartini dan Kaus Oblong: Awal Mula Renungan yang Tak Terduga
Contents
- 1 Kartini dan Kaus Oblong: Awal Mula Renungan yang Tak Terduga
- 2 Perempuan di Zaman Sekarang: Benarkah Sudah Merdeka?
- 3 Kartini di Dalam Diriku: Mencoba Berdiri, Meski Sering Tergoyah
- 4 Perempuan, Media Sosial, dan Beban Sempurna
- 5 Kenapa Hari Kartini Masih Relevan (Dan Harus Tetap Diperingati)
- 6 Warisan Kartini dalam Bentuk Nyata
- 7 Penutup: Semangat Kartini Tak Mati — Ia Hidup Dalam Kita
- 8 Author

Pertama Kali Mengenal Kartini (Dan Gagal Memahaminya)
Aku mengenal nama Kartini pertama kali dari buku cetak SD. “Raden Ajeng Kartini: Pahlawan Emansipasi Wanita.” Tapi waktu kecil, konsep emansipasi itu jujur saja… abstrak banget. Aku pikir, dia seperti versi perempuan dari Pangeran Diponegoro.
Tapi saat remaja, aku mulai membaca surat-suratnya — terutama kumpulan Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan waktu itu… aku nangis.
Bukan hanya karena isinya menyentuh, tapi karena kata-katanya begitu relevan. Tentang pendidikan. Tentang mimpi. Tentang perempuan yang ingin punya ruang untuk berpikir, bertanya, dan tumbuh — tanpa dikungkung adat dan stereotip.
Perempuan di Zaman Sekarang: Benarkah Sudah Merdeka?
Sering kali kita berpikir bahwa perjuangan Kartini sudah selesai. Sekarang perempuan bisa sekolah tinggi, punya karier, jadi menteri, bahkan presiden. Tapi benarkah itu berarti semuanya sudah setara?
Aku seorang manajer konten di perusahaan digital. Di atas kertas, aku punya gaji oke, status kerja stabil, dan suara dalam rapat. Tapi setiap kali aku tegas menyampaikan pendapat, ada yang bilang aku galak. Kalau rekan prianya yang bicara keras? Dibilang tegas.
Pernah suatu kali aku harus pulang terlambat karena lembur, dan tetangga bilang, “Kok pulang malam terus, Mbak? Kasihan suaminya ya.” Padahal suamiku juga kerja, dan nggak pernah ditanyain seperti itu.
Dari situ aku sadar, perjuangan belum selesai. Emansipasi bukan sekadar boleh sekolah atau kerja. Tapi juga soal cara masyarakat memandang perempuan. Dan kadang, ketidakadilan itu halus — seperti bisik-bisik atau senyum sinis.
Kartini di Dalam Diriku: Mencoba Berdiri, Meski Sering Tergoyah

Aku bukan aktivis. Tapi aku percaya perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dan aku percaya, setiap perempuan punya Kartini dalam dirinya.
Kartini dalam diriku adalah ketika aku memilih lanjut kuliah, walau banyak suara bilang lebih baik nikah muda.
Kartini dalam diriku adalah saat aku berani bilang “tidak” pada klien yang melecehkan secara verbal, meski itu berarti kehilangan proyek.
Kartini dalam diriku adalah ketika aku ajak adikku yang masih SMA untuk terus belajar, meski dia bilang, “Buat apa, Kak? Nanti juga jadi ibu rumah tangga.”
Dan kadang aku gagal juga. Kadang aku diam saat harusnya bersuara. Tapi aku terus belajar. Karena, seperti kata Kartini: “Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tidak mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi bawa keindahan.”
Perempuan, Media Sosial, dan Beban Sempurna
Satu hal lain yang aku rasa penting untuk dibahas di Hari Kartini adalah tekanan media sosial. Dulu, perempuan dibungkam oleh adat dan tradisi. Sekarang, kita dibungkam oleh standar “perempuan sempurna” di Instagram.
Aku pernah merasa rendah diri karena nggak bisa masak se-estetik food blogger. Pernah ngerasa nggak cukup kurus untuk ikutan tren OOTD. Pernah merasa gagal karena belum punya anak di usia tertentu.
Tapi aku mulai sadar: menjadi Kartini bukan berarti jadi sempurna. Tapi jadi autentik.
Dan sebagai blogger, aku mulai ubah cara nulis. Dari yang tadinya hanya konten viral, sekarang aku lebih suka berbagi kisah jujur — soal kegagalan, keraguan, bahkan rasa takut. Karena kadang, cerita nyata lebih menyembuhkan daripada motivasi palsu.
Kenapa Hari Kartini Masih Relevan (Dan Harus Tetap Diperingati)

Beberapa orang bilang, “Ah, Kartini kan hanya satu dari banyak tokoh perempuan. Kenapa harus terus dirayakan?”
Tapi menurutku, Hari Kartini bukan soal kultus individu. Tapi simbol.
Simbol bahwa perempuan juga bisa berpikir, bersuara, dan mengubah dunia — bahkan dari dalam kamar kecil, lewat surat, di masa ketika itu sangat mustahil.
Kartini mungkin sudah tiada, tapi semangatnya hidup dalam perempuan yang rela begadang demi skripsi. Dalam ibu rumah tangga yang sambil urus anak tetap sempat bikin usaha kecil-kecilan. Dalam guru honorer yang digaji kecil tapi tetap semangat mengajar, dikutip dari laman resmi Detik.
Warisan Kartini dalam Bentuk Nyata
Kalau kamu tanya, “Apa sih warisan Kartini yang paling terasa sekarang?” Jawabanku:
Pendidikan perempuan. Ini bukan cuma soal ijazah, tapi soal hak berpikir.
Kesetaraan di tempat kerja, meski masih banyak yang harus diperjuangkan.
Ruang untuk berdialog, karena suara perempuan sekarang lebih banyak didengar — di ruang rapat, podcast, sampai TikTok.
Kebebasan memilih jalan hidup, meski tak selalu bebas dari komentar orang.
Penutup: Semangat Kartini Tak Mati — Ia Hidup Dalam Kita
Di akhir tulisan ini, aku ingin bilang: Hari Kartini bukan cuma tentang bunga atau lomba kebaya. Tapi tentang keberanian jadi diri sendiri, meski melawan arus.
Setiap kali kamu bilang “tidak” saat semua orang bilang “iya”, kamu adalah Hari Kartini. Setiap kali kamu ajak perempuan lain tumbuh bersama, kamu adalah Kartini.
Hari Kartini bukan sejarah. Kartini adalah masa kini.
“Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan yang terus melangkah, meski dunia berkata diamlah.”
Baca Juga Artikel dari: Negosiasi Perdagangan: Dari Jualan Online Sampai Ngerti
Baca Juga Konten dengan Artikel Terkait Tentang: Culture